DERETAN – Pernah mendengar kalimat seperti, “Ah, itu urusan domestik, yang penting keluarga aman,” atau, “Selingkuh? Itu kan cuma teman lama dan luapan emosi sesaat”? Ungkapan-ungkapan yang dulu tabu untuk diucapkan secara terbuka, kini menjadi perbincangan biasa di ruang digital dan percakapan sehari-hari. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak lagi selalu dipandang sebagai aib yang memalukan, melainkan mulai diterima sebagai sebuah “keniscayaan” atau bagian wajar dari dinamika hubungan.
Lihatlah bagaimana kasus perselingkuhan figur publik dikonsumsi. Perhatian publik sering kali lebih tertuju pada perbandingan penampilan fisik atau drama percintaan, alih-alih pada inti persoalan: penghianatan terhadap janji dan kepercayaan. Kasus-kasus tersebut sering kali dikemas menjadi tontonan spektakuler layaknya sinetron nyata, yang justru mengaburkan dampak destruktifnya bagi semua pihak yang terlibat. Fokusnya bergeser menjadi sensasi, bukan substansi pelajaran moral.
Kenormalan yang palsu inilah yang justru berbahaya. Mengurangi kadar “salah” dalam perselingkuhan sama halnya dengan mengikis fondasi terpenting hubungan antarmanusia, yakni: komitmen dan kejujuran. Seperti diingatkan pakar etika, Michael J. Sandel dalam bukunya Justice: What’s the Right Thing to Do? (2009), “Masyarakat yang sehat membutuhkan rasa saling percaya, dan kepercayaan itu tumbuh dari komitmen yang dipenuhi, bukan dari janji yang diingkari.” Jika dibiarkan, proses tersebut tidak hanya mendangkalkan makna hubungan personal, tetapi lambat laun akan merusak jaringan sosial kita secara kolektif.
Anatomi Normalisasi Perselingkuhan
Normalisasi perselingkuhan paling nyata bermula dari perubahan kosakata kita. Istilah-istilah tegas dari ranah hukum dan agama seperti “berzinah” atau “mendua” semakin tergantikan oleh bahasa sehari-hari yang netral, bahkan cenderung bercanda, seperti “main-main”, “pelampiasan”, atau “side hustle“. Pergeseran linguistik tersebut bukanlah hal remeh. Menurut teori Relativitas Linguistik, yang dikembangkan oleh Edward Sapir (1929) dan Benjamin Lee Whorf (1956), bahasa yang kita gunakan membentuk cara kita memandang realitas. Ketika sebuah pelanggaran berat hanya disebut “main-main”, bobot moralnya akan menguap di benak publik, mengubahnya dari dosa menjadi sekadar ‘selingan’.
Media populer memainkan peran krusial dalam melunakkan pandangan kita. Banyak sinetron, film, maupun lagu yang menggambarkan perselingkuhan sebagai petualangan romantis penuh gairah, di mana pelaku sering tampil glamor dan terbebas dari konsekuensi sosial yang mendalam. Representasi yang bias ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori Cultivation (Gerbner & Gross, 1976), secara bertahap “membudidayakan” persepsi penonton bahwa perilaku tersebut lebih lumrah dan dapat diterima daripada kenyataannya. Akibatnya, batas antara fiksi dan realitas menjadi kabur, dan perselingkuhan direduksi menjadi bahan hiburan.
Melengkapi peran media, di tingkat masyarakat berkembang narasi-narasi pembenaran yang seolah memberi legitimasi logis. Ungkapan seperti “yang penting masih bertanggung jawab di rumah” atau “itu terjadi karena pasangan kurang perhatian“, berusaha merasionalisasi kesalahan dengan memindahkan sebagian tanggung jawab. Pada konteks budaya Indonesia yang mengedepankan harmoni dan “menjaga muka”, sering kali muncul justifikasi seperti “asal tidak ketahuan” atau “jangan sampai mempermalukan keluarga“.
Logika pembenaran sangat berbahaya karena menciptakan lingkaran menyalahkan yang mengikis akuntabilitas pribadi. Psikolog sosial Albert Bandura dalam konsep Moral Disengagement (Mekanisme Pembenaran Diri) yang diperkenalkan dalam bukunya Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory (1986), menjelaskan bagaimana individu melepaskan diri dari standar moral dengan mendistorsi akibat tindakannya dan menyalahkan korban. Narasi-narasi populer itulah wujud mekanisme yang kini ‘dilembagakan’ secara sosial, mengubah pengkhianatan dari pilihan keliru menjadi konsekuensi yang “wajar”.
Teknologi yang Memfasilitasi, Budaya yang Merasionalisasi
Perangkat digital telah mengubah perselingkuhan dari urusan fisik yang berisiko, menjadi transaksi digital yang nyaris tanpa jejak. Aplikasi percakapan rahasia dengan fitur end-to-end encryption dan disappearing messages, serta media sosial dengan fitur Direct Message (DM), menciptakan kanal rahasia yang memfasilitasi perselingkuhan emosional maupun fisik. Kemudahan akses tersebut secara teknis menurunkan threshold (ambang batas) untuk berkhianat, mengubahnya dari rencana rumit menjadi godaan sekali klik.
Fakta tersebut bukan hanya kesan, melainkan didukung data empiris dari berbagai tingkatan. Secara global, riset berulang kali menunjukkan korelasi antara intensitas penggunaan media sosial dan risiko perselingkuhan. Di tingkat nasional, survei terkait ketahanan keluarga di Indonesia pun melaporkan temuan yang serupa. Lebih spesifik, penelitian Alena et al. dalam Social Science Computer Review (2021) memperlihatkan bagaimana platform digital berperan sebagai enabler utama, dengan menyediakan lingkungan yang mudah, privat, dan penuh peluang bagi perilaku tersebut.
Tidak hanya memfasilitasi, media sosial juga menciptakan marketplace untuk validasi diri yang distortif. Pada kultur show off (pamer), daya tarik dan keberhasilan seseorang sering kali diukur dari jumlah like dan komentar pujian. Perselingkuhan bisa menjadi cara ekstrem untuk “membuktikan” daya tarik tersebut, di mana perhatian dari orang baru dianggap sebagai social proof yang berharga. Fenomena tersebut mencerminkan teori Attention Economy (Ekonomi Perhatian) yang digagas Thomas H. Davenport dan John C. Beck dalam The Attention Economy (2001), di mana perhatian adalah mata uang langka. Pada konteks ini, perselingkuhan menjadi salah satu strategi mengumpulkan “modal” perhatian, meskipun berasal dari sumber yang ‘beracun’ dan merusak hubungan inti.
Budaya konsumsi instan “gunakan dan buang” ternyata telah masuk ke dalam paradigma hubungan interpersonal. Pola pikir yang melihat pasangan atau hubungan sebagai “objek” yang bisa diganti saat bosan atau ditambah untuk variasi, mencerminkan logika pasar dalam ranah intim. Konsep ‘Liquid Love‘ oleh Zygmunt Bauman (2003) menggambarkan fenomena tersebut dengan tepat, di mana hubungan manusia di era modern menjadi cair, rapuh, dan lebih berfokus pada kepuasan diri daripada ikatan yang kokoh. Pada logika ini, komitmen dianggap membatasi kebebasan, sedangkan perselingkuhan dilihat sebagai perluasan pilihan konsumen, sebuah bentuk eksplorasi yang dijustifikasi oleh narasi pencarian jati diri atau kebahagiaan pribadi, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab kolektif.
Bahaya Tersembunyi di Balik Normalisasi
Ketika perselingkuhan dinormalisasi, korban utamanya (pasangan yang dikhianati) sering kali mengalami invalidation atas lukanya. Trauma psikologis seperti rasa dikhianati (betrayal trauma) dianggap tidak penting. Padahal, menurut penelitian Jennifer J. Freyd dalam Betrayal Trauma Theory (1996), pengkhianatan oleh orang yang dipercaya justru menyebabkan dampak yang lebih kompleks dan sulit dipulihkan.
Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa perselingkuhan sering menjadi akar atau pemicu signifikan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komnas Perempuan yang dalam berbagai kesempatan menyoroti keterkaitan erat antara perselingkuhan dan kekerasan psikis sebagai pola yang sering ditemui. Pada situasi tersebut, korban sering kali merasa dikhianati dua kali: oleh pasangan, dan oleh masyarakat yang meremehkan penderitaannya. Dampak berlapis tersebut akan meracuni fondasi kepercayaan di keluarga. Stabilitas rumah tangga akan runtuh bukan hanya oleh perselingkuhannya, tetapi oleh hilangnya pengakuan bahwa sebuah pelanggaran serius telah terjadi.
Dampak normalisasi tidak hanya berhenti di ruang privat, melainkan merembes ke ruang publik dan mengikis modal sosial terpenting, yakni: kepercayaan (social trust). Padahal, masyarakat dibangun dari jaringan kepercayaan, mulai dari ikatan intim hingga kontrak sosial yang paling formal. Sosiolog Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity (1995) menegaskan bahwa kemakmuran suatu masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan sosialnya. Jika pengkhianatan dalam ikatan paling privat (pernikahan) bisa dianggap biasa, maka secara bertahap, kepercayaan pada institusi yang lebih luas (tetangga, rekan kerja, atau pemerintah) juga menjadi rentan. Masyarakat akan berjalan dengan prinsip kecurigaan yang tinggi, di mana setiap janji dan komitmen diragukan integritasnya.
Tidak berhenti di tingkat sosial, dampak tersebut akan berlanjut ke generasi muda. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan di mana perselingkuhan dinormalisasi akan mewarisi persepsi yang terdistorsi tentang hubungan yang sehat. Akibatnya, mereka berisiko menginternalisasi bahwa komitmen adalah sesuatu yang fleksibel dan perselingkuhan merupakan konsekuensi yang dapat diterima.
Persepsi yang keliru tersebut dapat mengganggu perkembangan psikososial mereka. Psikolog perkembangan Erik Erikson dalam karyanya Childhood and Society (1950) merumuskan teori tahap psikososial yang menyebut bahwa masa dewasa awal merupakan periode kritis untuk membentuk kapasitas intimacy vs. isolation. Paparan normalisasi perselingkuhan dapat menghambat pencapaian keintiman, mendorong generasi muda memilih isolasi emosional atau hubungan yang superfisial karena takut dikhianati. Bukannya belajar menyelesaikan konflik, mereka mungkin mengadopsi mentalitas “ganti yang baru” yang pada akhirnya menghasilkan pola hubungan tidak stabil, tidak memuaskan, serta melanggengkan siklus ketidaksetiaan.
Merevitalisasi Etika Relasional
Menghadapi kondisi tersebut, langkah pertama melawan normalisasi adalah dengan berani menyebut kesalahan sebagai kesalahan. Sebab, menolak menormalisasi perselingkuhan bukanlah sikap sok suci, melainkan sebuah komitmen untuk menjaga kejelasan moral. Hanya dengan kejelasan moral, pertanggungjawaban dan rekonsiliasi tetap dimungkinkan. Filsuf moral, Kwame Anthony Appiah dalam bukunya The Honor Code: How Moral Revolutions Happen (2010), menekankan bahwa perubahan moral dimulai ketika suatu praktik tidak lagi dilihat sebagai hal yang terhormat. Dengan konsisten menolak eufemisme dan menyebutnya sebagai pengkhianatan, maka akan menciptakan norma sosial yang memulihkan kejelasan moral. Tanpa pengakuan, ruang untuk introspeksi dan rekonsiliasi akan tertutup oleh kabut rasionalisasi.
Perubahan norma harus dimulai dari lingkaran terdekat: komunitas dan percakapan sehari-hari. Kita perlu lebih kritis terhadap bahasa dan candaan yang mengecilkan korban atau membingkai pelaku sebagai ‘pencari cinta’. Sebab, menurut Teori Komunikasi Konstitutif (Craig, 1999), bahasa tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga secara aktif membentuk realitas dan nilai-nilai sosial kita. Oleh karena itu, setiap kali kita diam saat mendengar lelucon yang menormalisasi ketidaksetiaan, atau ikut menyebarkan gosip yang meromantisasi perselingkuhan, kita secara tidak langsung ikut membangun realitas sosial yang permisif. Sebaliknya, memilih kata-kata yang menghargai martabat semua pihak dan menegaskan pentingnya kesetiaan adalah bentuk perlawanan yang konkret dalam membentuk norma baru.
Masyarakat perlu mengalihkan energi dari menyaksikan drama “siapa vs siapa” menuju diskusi yang lebih substantif tentang membangun hubungan sehat. Publik harus diajak mendiskusikan literasi emosional, keterampilan komunikasi asertif, dan manajemen konflik, kompetensi yang justru sering absen dalam pendidikan. Psikolog John Gottman dalam bukunya The Seven Principles for Making Marriage Work (1999) mengidentifikasi bahwa tanda utama hubungan yang akan runtuh adalah budaya menghina, membela diri, menutup diri, dan mengkritik; bukan hanya adanya ketertarikan pada orang lain. Dengan fokus pada esensi membangun komitmen, kita dapat mengubah perselingkuhan dari hanya skandal, merevitalisasi menjadi sebuah kegagalan relasional yang bisa dipelajari dan dicegah.
Upaya menolak normalisasi perselingkuhan perlu didukung oleh kebijakan publik yang progresif. Langkah strategis pertama adalah melalui dunia pendidikan. Pemerintah perlu merumuskan materi pendidikan kehidupan berkeluarga yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi. Materi tersebut harus berfokus pada literasi emosional, etika hubungan, dan manajemen konflik sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga sejak dini.
Langkah strategis kedua terletak pada pengaturan ekosistem media. Pemerintah dapat memperkuat regulasi konten media yang meromantisasi perselingkuhan, serta secara aktif mendorong produksi konten yang mengedukasi tentang nilai kesetiaan dan kepercayaan. Solusi struktural dari hulu (pendidikan) hingga hilir (media) penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang konsisten mendukung, bukan merusak, komitmen dalam hubungan.
Membangun Kembali Komitmen Kolektif
Dari bahasanya yang tumpul hingga glorifikasinya di layar kaca, normalisasi perselingkuhan bukanlah bukti kemajuan berpikir. Sebaliknya, fenomena tersebut justru merupakan gejala kemunduran kolektif dalam menjaga nilai paling mendasar dari hubungan manusia: trust (kepercayaan) dan fidelity (kesetiaan). Sosiolog Émile Durkheim dalam konsep Anomie yang dikemukakan dalam karya klasiknya Le Suicide (1897), mendeskripsikan keadaan di mana norma-norma sosial melemah dan individu kehilangan pedoman, gejala yang kini tercermin ketika pelanggaran komitmen dianggap biasa. Menjadikan perselingkuhan sebagai sesuatu yang “wajar” bukanlah kebebasan, melainkan bentuk pelepasan tanggung jawab sosial yang berbahaya.
Perubahan harus dimulai dari kesadaran dan tindakan personal. Mulailah dengan mengevaluasi reaksi kita; beranilah menyatakan bahwa perselingkuhan adalah pelanggaran yang menyakitkan, bukan bahan canda atau gosip. Selanjutnya, kita perlu membangun budaya edukatif yang proaktif. Pada konteks budaya Indonesia yang kuat dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong, pendidikan tentang hubungan sehat dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan komunitas, seperti: pengajian, pertemuan PKK, atau karang taruna.
Psikolog Robert J. Sternberg dalam Triangular Theory of Love (1986) menegaskan bahwa cinta yang utuh membutuhkan kombinasi intimasi, gairah, dan komitmen. Pendidikan harus mengajarkan literasi hubungan sehat (termasuk konsep consent, komunikasi non-kekerasan, dan arti komitmen yang bertanggung jawab) kepada generasi muda sebagai bekal penting yang setara pendidikan akademis. Dengan fondasi pengetahuan yang kuat, menjaga integritas hubungan, maka dapat naik menjadi komitmen kolektif masyarakat. Menjaga keutuhan hubungan bukan berarti kembali kepada nilai patriarki yang kaku, melainkan membangun kesepakatan sosial baru untuk menghargai martabat dalam setiap ikatan relasional.
Ketika sebuah masyarakat mulai berhenti menganggap perselingkuhan sebagai suatu aib, hal itu bukanlah tanda kebebasan yang matang. Seperti yang diingatkan filsuf Aleksandr Solzhenitsyn dalam karya monumentalnya The Gulag Archipelago (1973), “Batas antara baik dan jahat tidak membelah dunia antara ‘kita’ dan ‘mereka’. Garis itu melintasi setiap hati manusia.” Justru, bisa jadi masyarakat sedang kehilangan kompas etis paling mendasar dalam membangun ikatan insani dan kepercayaan, dua fondasi yang tidak tergantikan dari setiap peradaban yang bermartabat dan berkelanjutan.
Penulis: Harry Yulianto – Akademisi STIE YPUP Makassar








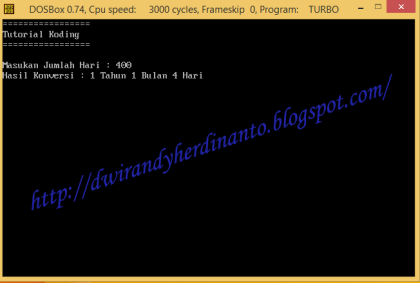















Komentar