DERETAN – Ketika kita bicara tentang lembaga legislatif, terutama DPR dan DPRD di Indonesia, ada satu fakta yang sering bikin dahi berkerut: syarat minimal pendidikan seorang anggota legislatif hanya ijazah SMA. Iya, kamu nggak salah baca. Lembaga yang tugasnya membuat hukum, justru tidak mewajibkan anggotanya memahami ilmu hukum secara mendalam. Ironi yang begitu nyata, sampai kadang kita bingung harus ketawa atau menangis.
Bayangkan seorang dokter yang boleh praktik hanya bermodalkan pelajaran Biologi SMA. Atau pilot yang cukup pernah naik pesawat waktu study tour. Absurd? Tapi untuk membuat undang-undang yang menentukan nasib 280 juta penduduk, tampaknya negara kita santai-santai saja dengan standar itu.
Padahal, DPR adalah jantung demokrasi yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang paham tata kelola negara, konstitusi, dan seluk-beluk peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya, kualitas anggota legislatif kita seringkali jauh dari ideal. Dan dampaknya? Ya sudah kita rasakan sama- sama.
Ketika Kebijakan Blunder Akhirnya Mendarat di Jalan Raya
Masyarakat masih ingat soal berbagai demonstrasi besar yang mewarnai perjalanan DPR belakangan ini. Bukan hanya soal UU yang kontroversial, tapi juga bagaimana chaos yang terjadi di lapangan.
Salah satu kejadian yang paling menyayat adalah insiden pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demo menolak RUU Omnibus Law. Rakyat turun ke jalan, menyampaikan suara mereka. Tapi malah ada yang kehilangan nyawa, bukan karena hukum yang merugikan, tapi karena proses penyampaiannya yang brutal.
Ada juga jurnalis yang dipukul, mahasiswa yang ditangkapi, dan gas air mata yang seakan jadi “bahasa resmi” pemerintah ketika rakyat meminta keadilan. Semua ini terjadi karena komunikasi politik yang buruk dan kebijakan yang tak memihak rakyat, yang lagi-lagi sumbernya berasal dari meja yang seharusnya berisi orang-orang terbaik.
Kualitas Kebijakan Ditentukan oleh Kualitas Pengetahuannya
Belum lama ini publik dibuat geleng-geleng kepala dengan pernyataan seorang pejabat tinggi soal program makan bergizi untuk siswa, yang mengatakan “makanan bergizi tidak perlu ahli gizi”. Lah, itu ibarat bilang bangun jembatan tak perlu insinyur, cukup tukang batu yang semangat kerja.
Pernyataan seperti itu bukan sekadar salah ucap. Itu merefleksikan minimnya kapasitas teknis dalam memahami kebijakan publik yang menyangkut kesehatan dan tumbuh kembang anak bangsa. Klaim ngawur itu akhirnya memicu kontroversi nasional hingga para ahli gizi, akademisi, organisasi profesi turun mengoreksi.
Ini jelas menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi di lingkaran kekuasaan dapat melahirkan kebijakan asal-asalan. Dan DPR sebagai pengawas pemerintah pun seringkali hanya mengangguk manis alih-alih mengkritisi secara ilmiah.
Jika memahami gizi saja tidak dianggap penting, bagaimana kita berharap mereka paham sistem hukum yang jauh lebih kompleks?
Blunder yang terlihat lucu di televisi itu sejatinya menyimpan bahaya besar:
Kebijakan publik tidak boleh bergantung pada opini pribadi, tapi pada ilmu pengetahuan. Saat ilmu ditinggalkan, rakyat yang menanggung akibatnya.
Fenomena Legislator Bingung dengan Tugas Sendiri
Dari DPRD kabupaten sampai DPR RI, kita sudah berkali-kali disuguhi tontonan yang kadang lebih lucu daripada stand-up comedy:
- Ada anggota DPRD tidur saat rapat penting.
- Ada yang tidak tahu perbedaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
- Ada yang asal tanda tangan RUU tanpa membaca isinya.
- Ada juga yang sibuk konten sosial media saat rapat.
Belum lagi kasus-kasus korupsi berjamaah di DPRD hingga dari Suap APBD, korupsi pokir (Pokok Pikiran), sampai jual-beli jabatan kepala daerah yang difasilitasi wakil rakyat. Mirisnya, banyak dari mereka bahkan baru paham pasal-pasal pidana ketika sudah menjadi terdakwa.
Kalau begitu siapa yang seharusnya mengawasi wakil rakyat? Rakyat lagi. Padahal kita sudah capek setiap lima tahun memilih.
RUU Penting Terbengkalai, yang Tak Penting Justru Dikebut
Coba kita tengok RUU Perampasan Aset, sebuah regulasi yang sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Sudah berkali-kali masuk Prolegnas, tapi entah mengapa selalu saja tertunda.
Negara rugi ratusan triliun akibat korupsi tiap tahun. Tapi DPR seolah menganggap RUU ini bukan prioritas. Kenapa? Banyak analis bilang, mungkin karena UU ini terlalu tajam untuk kepentingan para elite. Kalau aset bisa langsung dirampas tanpa menunggu vonis, ya bisa repot banyak orang.
Anehnya, saat mengesahkan UU yang pro-investor atau pro-oligarki, kecepatannya melebihi WiFi kampus, tap tap tap sah! Bahkan kadang dalam semalam.
Rakyat tepok jidat berjamaah.
Kepercayaan Publik Jatuh Bebas
Berbagai lembaga survei menunjukkan tren yang konsisten: DPR termasuk lembaga dengan tingkat
kepercayaan terendah di Indonesia. Tidak perlu data canggih untuk memahami alasannya:
- Kinerja legislasi yang buruk
- Banyak anggota terjerat kasus hukum
- Tidak aspiratif
- Kurang peka terhadap penderitaan rakyat
Ketika wakil rakyat lebih sibuk berdebat soal jatah kursi pimpinan daripada memperbaiki UU yang
merugikan rakyat, jelas kepercayaan publik makin terkikis.
Ketidaksiapan Pengetahuan Legislator, Bahaya untuk Bangsa
Dalam proses membuat aturan, tanyanya bukan cuma “bisa baca atau tidak”, tapi:
- Mengerti asas pembentukan peraturan perundang-undangan?
- Paham implikasi hukum secara sistemik?
- Mampu mengantisipasi celah hukum yang berpotensi disalahgunakan?
- Siap mempertanggungjawabkan keputusan secara etis?
Karena sebuah pasal keliru bukan berarti besok tinggal dihapus—bisa berakibat pada hilangnya:
- Hak buruh
- Ruang hidup masyarakat adat
- Akses rakyat kecil pada sumber daya ala
- Kebebasan berpendapat
Negara bisa mundur hanya oleh tinta dari tangan yang tak mengerti apa yang ia tanda tangani.
Saatnya Standar Lebih Tinggi untuk Wakil Rakyat
Maka, pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama:
Apakah masih pantas lembaga pembuat undang-undang direkrut dengan syarat minimal yang bahkan tidak cocok untuk pekerjaan administrasi dasar di banyak perusahaan?
Bukan soal merendahkan lulusan SMA. Banyak dari mereka sangat cerdas dan kerja keras. Tapi fungsi legislatif menuntut standar keahlian tertentu.
Setidaknya, syarat tambahan ini perlu dipikirkan:
- Pendidikan minimal D4/S1, terutama yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, atau hukum
- Tes kompetensi hukum dasar dan penyusunan kebijakan publik
- Pelatihan wajib legislasi berkelanjutan
- Penilaian etika berkala dan terbuka
Kalau rakyat saja yang mengurus administrasi KTP harus melewati proses berlapis dan berjam-jam, masa pembuat UU cuma lewat “belanja suara” saat pemilu?
Agar Demokrasi Tidak Sekadar Konten Kampanye
DPR seharusnya jadi simbol kehormatan. Tempat orang-orang terbaik bangsa berkumpul untuk merumuskan masa depan. Tapi tanpa reformasi kualitas, kita hanya akan melahirkan siklus kebijakan buruk.
Rakyat sudah terlalu sering dijadikan objek eksperimen oleh undang-undang yang gagal memahami realitas sosial. Demokrasi cacat ketika hukum tak berpihak pada kebenaran.
Di tengah semua kekecewaan, harapan tetap harus hidup:
Kita berhak menuntut wakil rakyat yang benar-benar layak disebut wakil rakyat. Bukan wakil partai. Bukan wakil kepentingan pemodal.
Apalagi wakil dari ketidaktahuan yang diformalkan.
Jika DPR adalah panggung besar bangsa, maka hentikan menjadikannya komedi gelap. Karena harga dari kebodohan di parlemen, dibayar oleh seluruh warga negara.
Dan itu terlalu mahal.
Penulis : Ade Yoga Pradesta – Fakultas Hukum – Universitas Bangka Belitung,





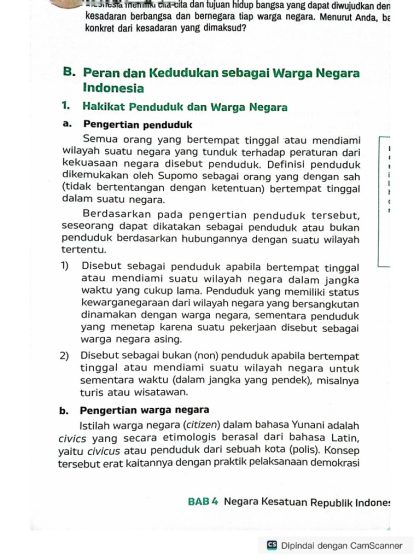




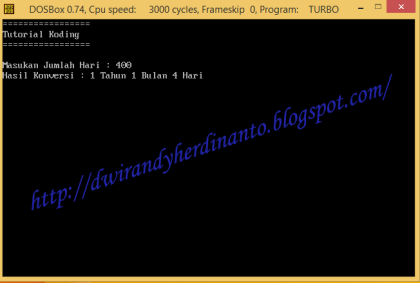














Komentar